Menggali Akar Kekerasan Seksual di Waingapu: Normalisasi Konten Seksis di Media Sosial sebagai Pemicu yang Terabaikan?
Beberapa waktu lalu, sebuah postingan tentang angka kekerasan di Sumba Timur menarik perhatian saya. Sebelum postingan dalam bentuk video ini dibagikan di media sosial oleh pengguna Facebook Pro, pada 5 April lalu saya sempat bertanya pada kk Rambu Dai Mami, ketika ia menuliskan status tentang 45,5% penghuni rumah tahanan Waingapu adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Itu artinya, dari 191 tahanan di Sumba Timur, 87 di antaranya terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Angka ini menggambarkan situasi yang sangat mengkhawatirkan.
Saya tidak ingin membicarakan betapa mengerikannya angka-angka tersebut. Kita tahu, bahwa melihat angka yang sangat amat tinggi itu, Sumba Timur, yakin saya, sudah darurat kekerasan seksual. Namun, dlam tulisan ini, saya tidak ingin membicarakan angka-angka itu. Saya ingin membicararakan hal yang lain, yang, menurut saya, memiliki pengaruh besar terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (di Waingapu): normalisasi konten berbau seksis di media sosial.
Mari kita mulai tulisan ini dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan jenis ini merujuk pada tindakan di ruang digital yang merendahkan, melecehkan, atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan gender, terutama perempuan dan anak. Contohnya meliputi komentar seksis, meme yang mengobjektifikasi tubuh perempuan, atau video yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga, sebagai lelucon. Saya sendiri lebih sering menemukan ini pada postingan-postingan foto para pengguna Facebook Pro penghamba dollar. Ini yang ada dalam friend list saya.
Laporan SAFEnet tahun 2023 menunjukkan peningkatan kasus KBGO di Indonesia sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 60% korban adalah perempuan muda berusia 15-25 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa isu KBGO perlu mendapatkan perhatian lebih serius, terutama terkait dengan korban perempuan muda yang rentan. Di Waingapu, saya tidak menemukan data spesifik tentang KBGO, tetapi melihat akses masyarakat terhadap media sosial, khususnya Facebook Pro yang terus meningkat, peluang penyebaran konten seksis terbuka lebar. #fyp seperti kata para pejuang 0,01.
Lucunya, masih di tempat yang sama, hal ini menjadi wajar. Sebab, banyak orang melakukan hal yang sama. Tujuannya jelas, demi insight yang besar. Kalau kata bapa dosen, Retang Wohangara dalam balasan komentarnya dengan SOPAN Sumba, sih, "menjamurnya kegilaan buat konten yang tidak jarang seksis, misoginis, stereotypical yang tujuannya mungkin dijadikan lelucon bisa sangat berbahaya. Konten sejenis ini dapat dengan mudah dikunyah sebagai kenormalan di dunia nyata."
Misalnya, lagi-lagi saya ambil contoh postingan dari pengguna Facebook Pro, tidak hanya satu orang, yang cenderung menggunakan foto seksis di mana mereka mempermalukan perempuan karena pakaiannya atau komentar yang merendahkan kemampuan perempuan sering kali dianggap hanya candaan semata. Sesungguhnya, konten jenis ini memperkuat budaya patriarki dan menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar.
Studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% konten berbasis gender di media sosial Indonesia mengandung unsur stereotip atau pelecehan ringan yang dianggap lucu oleh pengguna. Ini menandakan bahwa konten yang mempromosikan stereotip gender dan pelecehan, meskipun ringan, masih marak di media sosial Indonesia dan dianggap sebagai hiburan oleh sebagian besar pengguna.
Di Waingapu, di mana literasi digital kita masih terbatas, masyarakat pengguna Facebook Pro sering kali tidak menyadari dampak jangka panjang dari konten ini. Paling tidak, yang paling instan kita dapat dari konten jenis ini adalah pola pikir kita yang terbentuk untuk menormalisasi seksisme. Hal ini saya konfirmasi langsung dari pandangan pembuat konten jenis ini ketika mendapatkan kritikan. Misalnya, dengan mengatakan bahwa Facebook seharusnya memberikan teguran pada mereka jika mereka melanggar atau pemberi kritik adalah satpam media sosial. Ah, sesesat ini rupanya pola pikir kita. Belum lagi dukungan dari orang-orang, yang, hanya karena sudah berteman lama, entah itu di media sosial atau di kehidupan nyata, malah memilih membela mereka dengan membabi buta.
Normalisasi konten seksis di media sosial bukanlah masalah terisolasi. Ini adalah bagian dari siklus yang memperburuk kekerasan seksual di dunia nyata. Bayangkan! Sebuah foto seksis yang dibagikan ribuan kali dapat membuat pelaku merasa berhak untuk melecehkan orang lain, baik secara verbal maupun fisik. Sebuah studi yang pernah saya baca beberapa waktu lalu (saya lupa dari universitas mana), menemukan bahwa paparan konten misoginis di media sosial meningkatkan kemungkinan perilaku agresif terhadap perempuan sebesar 25% pada kelompok usia 18-30 tahun. Di Waingapu, di mana budaya patriarki masih sangat kental, konten jenis ini bisa menjadi bahan bakar yang memperparah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Untuk memutus siklus ini, kita perlu pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak. Salah satunya dengan melibatkan para konten kreator Facebook Pro untuk turut terlibat dalam edukasi literasi digital. Mereka, sesungguhnya adalah orang berakal, yang bukannya tidak paham akan hal ini, hanya saja, godaan dolar dari Facebook tidak bisa tertahan. Saya membayangkan ketika mereka memberi edukasi hari ini, pada satu orang pembaca postingan mereka, lalu dibagikan ke beberapa grup, yang disadarkan bukan hanya satu orang. Banyak!
Ah, sepertinya ini kepanjangan. Saya mau makan dulu. Yang jelas, kekerasan seksual di Waingapu bukan hanya tentang angka 87 dari 191 tahanan. Ini tentang budaya yang kita biarkan tumbuh, termasuk melalui konten seksis yang kita anggap biasa di media sosial.
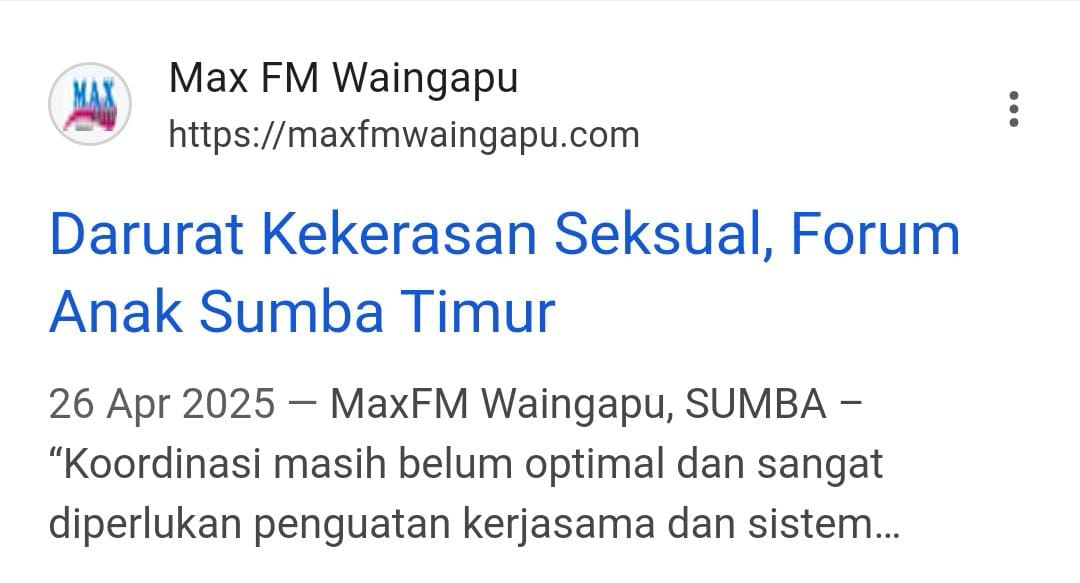


Comments
Post a Comment