Membaca BELIS sebagai Suatu Kemarahan
Tanggapan atas tulisan Nenansi Grasiani
Saya membaca tulisan seorang teman yang berjudul BELIS. Benar, judul tersebut ditulis dengan huruf kapital, lalu diberi keterangan agar pembaca membacanya tanpa menggunakan emosi. Saya membaca tulisan ini sekali, kemarin. Lalu, sekali lagi ketika ingin menuliskan ini. Dan, sekali lagi ketika selesai bertemu penulisnya.
Kepada para pembaca, kata "jangan pakai emosi," diperintahkan. Lalu, ketika saya membaca tulisan ini berkali-kali. Ada emosi di dalamnya. Ada gelora yang membara. Ada sesuatu, yang, memang kalau dibaca membuat hati berdebar. Secara keseluruhan, ini adalah tulisan dengan nada emosional yang kuat, ditulis dari perspektif feminis dengan kemarahan terhadap sistem yang merugikan perempuan. Pesannya jelas: perempuan tidak butuh belis untuk membuktikan nilai mereka, dan mereka tidak seharusnya diperlakukan sebagai properti hanya karena ada transaksi dalam pernikahan. Eits, tunggu dulu. Kau hanya akan merasakan itu bila kau paham bagaimana patriarki meninabobokan dirimu.
"Mengapa perempuan menjadi alat bantu setelah melepas masa lajang? Orang menyebut bahwa belis adalah alasan. Belis menurut pemikiran beberapa orang, adalah harga yang harus dibayar untuk membeli perempuan. Itulah kenapa setelah dibelis, dengan sendirinya hak bicara perempuan ditiadakan. Perempuan diwajibkan mengikuti semua aturan yang dirumuskan sepihak oleh pihak laki-laki. Orang-orang melihat posisi laki-laki sebagai korban dari belis, bahwa laki-laki dituntut berlebihan dan tidak wajar. Belis kemudian dijadikan sebagai identitas yang melekati tubuh seorang perempuan. Padahal, jika mereka rajin untuk menemukan akar dari mana harga dan ketentuan belis ini ditetapkan, itu asalnya dari para laki-laki. Jadi, kedudukan laki-laki sesungguhnya dari konteks belis ini bukanlah korban dari si perempuan." Demikianlah tulisan N_untuk menunjukkan betapa belis itu hanya sekadar mahar.
Tulisan ini adalah sebuah kritik tajam terhadap konsep belis—praktik pemberian mas kawin atau harga pengantin atau mahar dalam beberapa budaya di Indonesia, khususnya di NTT. Penulis menyoroti bagaimana belis sering kali dijadikan alasan untuk memperlakukan perempuan sebagai "benda" atau "alat bantu" dalam rumah tangga, alih-alih sebagai individu dengan hak dan suara.
Lihat saja di lingkungan sekitar kita yang begitu patriarki. Setelah menikah, yang menjalani kehidupan baru adalah perempuan. Laki-laki akan kembali ke kehidupannya seperti biasa. Ada yang keluar rumah sampai larut malam. Ada yang main judi. Ada duduk-duduk nongkrong berlama-lama dengan teman. Ada yang main game sampai larut malam. Ada yang cari teman untuk minum mabok dll. Perempuan? Di rumah. Masak. Urus rumah tangga. Jaga anak. Beberes rumah. Rutinitas hariannya kira-kira dimulai dari bangun pagi, beberes, bikin kopi, cuci, jaga anak, bikin makan, lalu diulangi terus. Sesekali keluar rumah, lalu kembali dengan rutinitas yang tetap. Di rumah. Sedangkan rutinitas laki-laki akan menyesuaikan.
Membaca tulisan tersebut, saya sesungguhnya ingin membalas singkat: siapa suruh cari yang patriarki? Namun, singkatnya jawaban itu tidak sesederhana yang saya pikirkan. Ada pertaruhan di dalamnya. Ada pertarungan di dalamnya. Perempuan vs laki-laki. Perempuan vs perempuan. Ada sesuatu yang kompleks di dalamnya.
"Lain kali, jangan kau bilang belis ini media untuk menegaskan harga dan nilai perempuan. Heh, supaya kau tau, Perempuan itu sudah bernilai sejak dia lahir sebagai perempuan. Kami tidak butuh dibelis dengan uang lu yang lu keluarkan dengan sungut-sungut itu hanya untuk menegaskan bahwa kami bernilai. Kami perempuan ini, sudah sangat mahal dan berharga, dengan atau tanpa lu bayar belis sekalipun. Jangan juga bilang belis adalah media untuk "mengeruk" kekayaan laki-laki...,"
Penulis, ingin menentang pemahaman bahwa belis adalah cara menentukan nilai perempuan dan membongkar bagaimana sistem ini sering kali dijadikan alat kontrol atas perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Di banyak budaya di NTT, belis memang bukan sekadar mahar, tetapi juga simbol status sosial keluarga perempuan. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering membuat perempuan kehilangan hak dalam pernikahan, seolah mereka "dibeli" dan harus patuh sepenuhnya pada suami dan keluarganya. Inilah yang dikritik penulis—bahwa perempuan dalam pernikahan masih diperlakukan sebagai "alat bantu" dan kehilangan posisi sebagai individu yang setara.
Bukankah untuk mendapatkan perlakuan yang setara, bisa dimulai dari menentukan pasangan yang setara? Barangkali, penulis bisa memulainya dari sini hehe
Eh, kembali ke topik.
Tulisan ini juga menantang pemikiran bahwa laki-laki adalah "korban" karena harus membayar belis. Padahal, aturan belis justru dibuat oleh laki-laki, dan sering kali yang diuntungkan bukan perempuan dan ibunya, melainkan ayah atau paman dalam keluarga. Kalau boleh ditambahkan, juga di dalamnya ada keluarga perempuan-ibu dari perempatan yang akan dibelis.
Bagaimana agar penulis tidak marah-marah pada sesuatu yang mengakar sejak dulu kala?
Sepertinya, mau tidak mau, saya memang harus kembali pada intermezzo di atas: harus dimulai dari mencari pasangan yang setara. Mencari pasangan yang setara adalah cara terbaik untuk terhindar dari budaya patriarki yang masih kuat. Jika dalam rumah tangga ada kesetaraan, maka pola pikir dan praktik diskriminatif bisa mulai terkikis dari lingkup paling kecil, yaitu keluarga. Apalagi, dalam membangun hubungan yang setara, yang dikedepankan adalah perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Dengan perspektif GEDSI, keputusan dalam keluarga tidak lagi didasarkan pada hierarki gender yang kaku, tetapi pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Misalnya, pembagian tugas rumah tangga yang adil, tidak otomatis dibebankan pada perempuan, sehingga perempuan sebagai istri tidak lagi dianggap sebagai pembantu laki-laki. Pengambilan keputusan bersama dalam keluarga, tanpa dominasi satu pihak. Hal ini bisa dimulai dengan poling bersama dan menentukan suara mayoritas adalah pemenangnya. Dan, yang tak kalah pentingnya adalah, jika dalam kehidupan rumah tangga itu sudah memiliki anak, maka wajib hukumnya untuk menanamkan nilai kesetaraan kepada anak-anak agar generasi berikutnya tidak lagi melanggengkan patriarki seperti yang ditulis dengan penuh emosi oleh penulis BELIS tersebut.
Dan, saya kira, salah satu cara untuk mendapatkan itu semua adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah cara berpikir masyarakat tentang kesetaraan gender, termasuk dalam konteks belis dan pernikahan di NTT. Pendidikan yang baik bisa membuka wawasan, mengubah pola pikir yang sudah mengakar, dan mendorong generasi muda untuk membangun hubungan yang lebih setara. Kemudian, yang paling penting adalah, dengan pendidikan, kita juga bisa marah-marah seperti penulis BELIS ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai universal yang dianut.
Tulisan ini belum selesai, tapi saya sudah capek. Kapan-kapan saya lanjutkan dengan lebih singkat lagi.

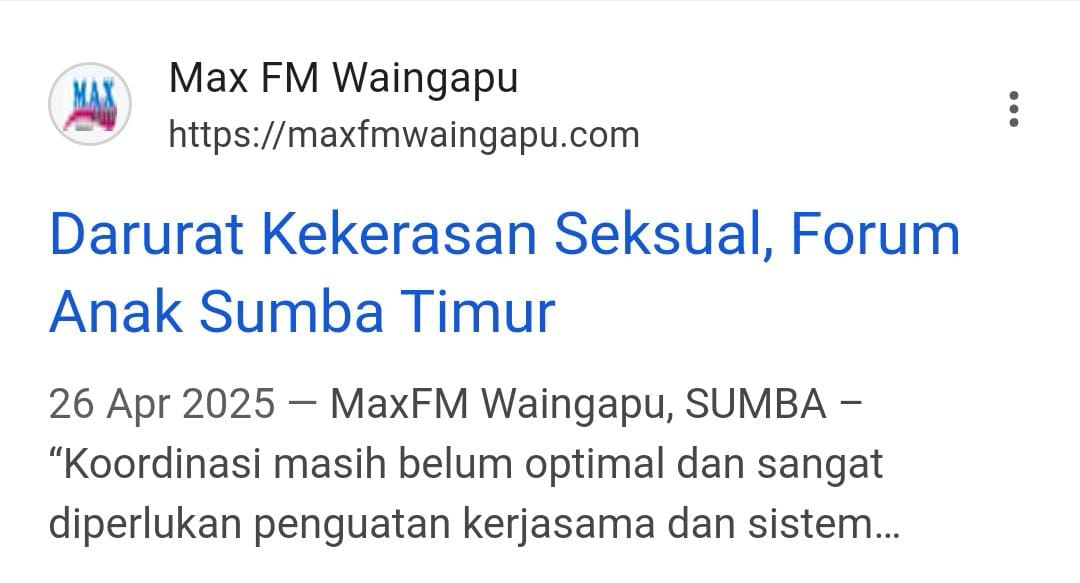

Comments
Post a Comment