untuk S(aya)
Aku masih ingat, beberapa waktu lalu, aku sempat membaca penggalan puisi yang pernah kau buat untukku. Kata-katanya sama persis dengan yang pernah terkirim lewat Short Message Service, kala jaringan seluler hanya mengizinkanmu berkirim pesan lewat SMS. Geser sedikit mati, kata orang-orang membuat akronim sembarang dari GSM, tapi tidak demikian dengan hp senter yang selalu penuh dengan signal hingga membuatmu sempat-sempatnya berkirim puisi.
"Jika nanti temu kita untuk seteru, maka biarkan itu menjadi candu
Percakapan kita adalah sayap bagi kupu-kupu yang bermain di antara tembok bisu
Kelak, saat kita menjadi asing di bibir kota
Jangan lupa, pada pengirim doa selepas hujan sore mereda
Sebelum jumat melipat kamis, doa akan bertandang, lalu-lalang harapan sebelum kau berbaring...
Selepas hening hujan di sana dan dunia terasa kosong
Pada jarak yang tidak kau ketahui, tersenyumlah untuk menghangatkan kesedihan doa-doa
2020,"
10 Desember 2020. Kulengkapi sekalian dengan tanggal puisi ini kuperoleh darimu.
Aku masih menyimpan percakapan kita tahun 2020 lalu, saat kita saling sepakat untuk memblokir segala akses penghubung antara kita di media sosial. "Sebaiknya, kamu jangan menghubungiku," katamu. Lalu kita memutuskan untuk saling blokir. Tentu saja ini terjadi setelah perdebatan kecil, yang, tidak benar-benar keluar dari hatimu. "Saya tidak masalah dengan ini. Bahkan, tanpa komunikasi pun, kita semua sudah terbiasa."
Sebelum benar-benar memblokirku, kau masih sempat-sempatnya berpesan, "saya senang kita berteman. Lagi pula, kapan lagi bisa punya kawan bacot yang perhatian dengan hal-hal yang kita suka? Sekalipun kerap menyebalkan, tapi tolong, jangan merasa diperebutkan."
Setahun berlalu, aku benar-benar kehilangan segala akses yang menghubungkan kita. Saat ulang tahunmu, sebuah pesan WhatsApp sengaja kukirim untukmu. Sebuah pesan ke sekian yang berakhir hanya dengan centang satu, nyaris mati sebab yang dituju sudah tanpa foto profil.
Dua tahun berlalu, kehilangan-kehilang yang tak hilang itu nyaris menghukumku dengan semua rasa bersalah. Namun, puisimu masih melayang-layang. Di ingatan. Di pikiran. Di mana-mana saat kesunyian melanda. Setidaknya, itu adalah satu-satunya jalan menemuimu tanpa temu. Barangkali benar katamu, "puisi yang saya buat untukmu itu, saya baca banyak-banyak buku, baru itu tulisan jadi. Tidak spontan-spontan amat. Saya harus hayati dan bikin baik-baik." Puisinya tetap tinggal meski orangnya pergi.
2023, entah berapa hari terlewati, tiba-tiba story WhatsApp-mu muncul. Seakan tidak percaya, aku lalu membalasnya. Jawabanmu dingin. Seperti es batu yang baru dikeluarkan dari freezer. Meski demikian, aku masih sama, menjadi salah satu dari sekian banyak pengagum puisi-puisimu, yang tetap membacanya meski lebih dari setahun kehilangan akses, yang berusaha mendapat suguhan puisi yang sudah jarang itu.
Jika harus berperan, maka pesan yang inginku sampaikan adalah, "kita boleh dingin, tapi puisimu harus tetap hidup." Tetaplah hidup, setidaknya dalam puisi. Sebab katamu, "puisi selalu bisa jadi amunisi." Karena itu, untuk mengakhiri surat yang bukan surat ini, sekali lagi, boleh kupinjam puisimu yang lain? Yang pernah kau tulis juga untukku:
"Kita adalah akhir tanpa jawaban
Melilit hati dengan tali penuh cobaan
Kita adalah awal tanpa dimulai
Membuat kisah yang mesti diakhiri."
Maaf dan terima kasih.


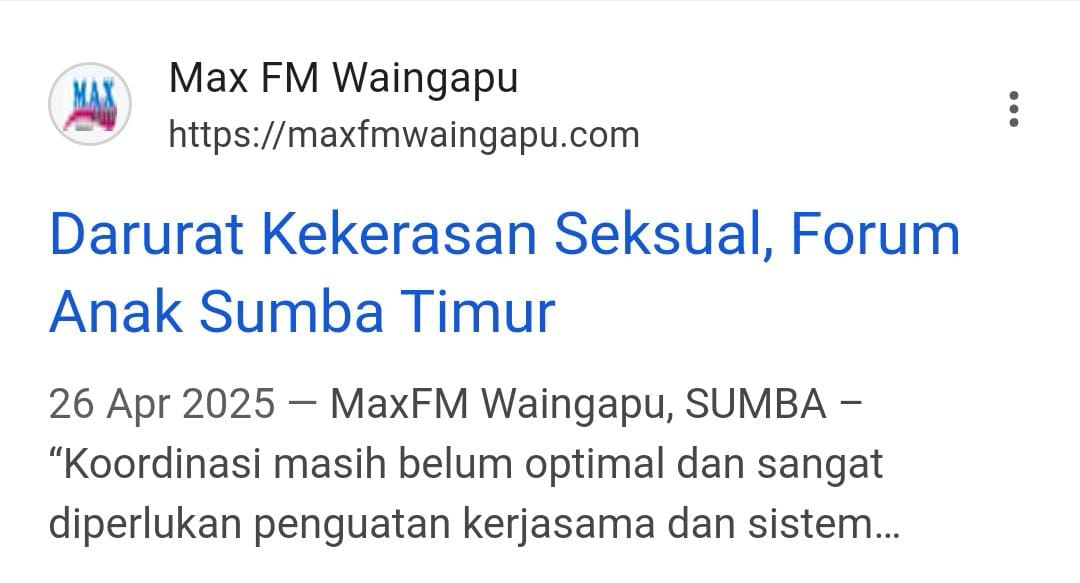

Comments
Post a Comment