Humba yang Tersisa di Kepala
Saya kemudian mereka-reka apa itu penghargaan, sebagai orang Sumba?
Barangkali, ia datang seperti seekor kuda, yang dibalas dengan seekor babi. Barangkali, ia hanya sepotong kain, yang dibalas dengan tikaman babi. Barangkali ia hanya sebuah Mamuli, yang dibalas dengan duduk lebih lama lagi. Ma'ta ka ta-patembi wangu, bha wa'da dha makawiadha². Supaya kita saling menghargai seperti kata tetua².
Singkatnya, patembi ini adalah fondasi penting yang menentukan cara masyarakat Sumba, seperti saya ini, untuk saling berhubungan dan menjalankan kehidupan adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Dan, sebagai orang Sumba, saya telah kehilangan banyak ke-Sumba-an saya. Saya tidak percaya lagi dengan kalimat toksisitas positif semacam, nda Humba li la mohu aka-ma³. Kami bukan Sumba yang menuju kepunahan³. Sebab, makin ke sini, ini hanyalah keyakinan yang memaksakan diri untuk selalu bersikap positif dan menolak semua emosi negatif, meskipun situasinya sulit.
Bicara kepunahan, bahasa adalah salah satunya yang menuju ke sana. Tahun 2022, dalam catatan yang pernah saya posting, saya menulis jumlah bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi sebanyak 38 yang tersebar di 12 provinsi. Di NTT, salah satu dari 5 bahasa daerah yang akan menjadi objek revitalisasi adalah Hi'lu Humba Kambiara⁴. Bahasa Sumba Kambera⁴. Itulah sebabnya ada program revitalisasi bahasa daerah, yang, ya, begitulah, menteri penggagasnya sudah di bui.
Bahasa ini, kan, difungsikan untuk berkomunikasi. Kalau dia tidak difungsikan untuk komunikasi, lalu apa? Pertanyaan itu muncul saat saya berdiskusi dengan k Diana Timoria. Pertanyaan demi pertanyaan ia lontarkan. Kau pernah tidak punya teman orang Manggarai? Atau bergaul dengan anak Manggarai. Anak seusiamu. Kau lihat tidak? Pola mereka menggunakan bahasa daerah. Mereka itu di mana saja, mereka dengan mudah, bahkan kadang saya menangkap kesan bangga di mereka kalau mereka pakai bahasa daerah ke sesamanya mereka, walaupun akibatnya adalah mereka mengabaikan atau membuat kita yang lain berkecil hati karena tidak memahami apa yang mereka omong. Tapi mereka tetap omong itu, begitu.
Sementara itu, yang saya lihat di teman-teman Sumba, bahkan bila itu di organisasi yang nama organisasinya ada Sumba di dalamnya, tidak seperti itu, tidak menggunakan Bahasa Sumba itu sendiri. Sekalipun ke sesama Sumba Timur dan lain sebagainya. Kalau di kampung-kampung, mungkin iya, orang masih pakai.
Bahkan generasi-generasi saya, kata k Diana, misalnya yang kemudian sudah kuliah, atau pernah sekolah, itu sudah jarang menggunakan bahasa daerah. Kalau di kampung-kampung, mungkin iya, orang masih pakai. Sebenarnya banyak hal sih, contoh hal-hal yang punah. Bahasa termasuk, kan? Sudah banyak penelitian yang bilang soal bagaimana sebenarnya bahasa itu. Maksudnya beberapa bahasa lokal di Indonesia punah atau sebenarnya ada ritual-ritual yang sebenarnya sudah tidak lagi dilakukan, misalnya.
Ada hal-hal yang sudah tidak dilakukan karena, katakanlah karena zaman atau karena apalah. Bahasa Inggris, misalnya. Dulu, kan, orang-orang tidak menggunakan bahasa Inggris, sekarang orang menggunakan bahasa Inggris. Jadi, ada kekuatan dari luar, yang mempengaruhi apa-apa yang ada di suatu tempat. Bisa jadi pengaruhnya kuat, bisa jadi tidak. Tergantung bagaimana tempat itu.
Saya ingat, di tahun yang sama saat saya menulis itu, sebuah grup WA dibuat oleh Ama⁵ Umbu Hunga Meha Tarap. Bapak⁵. Saya memanggilnya dengan sebutan Ama, sebab Hunga adalah nama bapak saya juga. Jadi, ya, ini pas. Grup WA itu bernama Hìlu Humba Kambera, beranggotakan orang-orang yang sadar akan pentingnya bahasa Sumba. Ada banyak gagasan dalam grup itu, yang lahir dari rahim orang-orang Sumba, yang peduli pada keberlangsungan bahasa Kambera. Sayangnya, kesibukan membuat kami semua jarang aktif.
Saya senang, karena dapat terhubung dengan orang-orang dalam grup yang anggotanya berjumlah 44 orang, termasuk saya itu. Saya senang karena di sana saya belajar banyak hal tentang bahasa Sumba, yang, saya sendiri banyak tidak tahunya. Saya senang, karena grup ini telah digagas dengan gagah, tanpa adanya keinginan untuk menyaingi program revitalisasi bahasa daerah yang dibuat pemerintah. Kami ingin menjaga yang tersisa. Saya senang, dan akan lebih senang, jika grup ini hidup kembali.
Sebagai anak muda yang cukup melek dengan media sosial, saya ingin ini menjadi awal bagi kami, generasi muda, untuk belajar, berbenah dan mempertahankan bahasa Sumba dari ancaman kepunahan. Sebab, ancaman itu bukan hanya pada bahasa, tapi juga pada nama. Saya membayangkan ini ketika menanyai beberapa anak. Bayangkan! dari sepuluh anak yang saya tanyai, hanya ada satu yang namanya adalah nama orang Sumba. Sisanya adalah nama-nama pemberian ketika dibabtis.
Saya ingat, beberapa bulan lalu, saya pernah berdiskusi dengan bapa dosen, Retang Wohangara, tentang kepunahan ini. Ia menerangkan bahwa, nama Retang sudah melekat padanya sejak tahun 90-an. Sebab, nama adalah identitas. Identitas yang menandai dari mana kita berasal siapa yang memberi kita nama, dan bahasa apa yang pertama kali menyebut kita manusia. Identitas kita sebagai orang Sumba, juga melekat dalam bentuk nama.
Ah, kepala saya sudah sakit ketika menulis ini. Sepertinya saya terlalu jauh memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak saya pikirkan. Saya akan kembali pada undangan tadi. Saya tidak suka keramaian. Isi kepala saya sudah terlanjur ramai. Banyak hal berlalu-lalang di dalamnya, seperti kendaraan di jalanan yang tidak pernah tidur. Mereka berdesakan, menabrak satu sama lain, lalu menghilang tanpa jejak. Ketika mereka memberontak ingin keluar, tetap saja tanpa wujud.
Isi kepala saya memang begini-begini saja. Ada berjuta-juta pengandaian. Ada beberapa orang. Biasa saja. Dari dulu sudah begini adanya. Entah mengapa? Saat menerima undangan digital ini, saya merasa seperti sedang diingatkan lagi, betapa banyak hal telah berubah dan betapa sedikit yang tersisa dari saya yang dulu. Namun, tetap dengan bangga saya katakan, ambu lupa ta pa-ho mangu umangu la u'ma wiki-nda⁶. Supaya kita tidak bertamu di rumah sendiri.
Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Sebab, kepunahan apapun, baik rumah adat, bahasa daerah maupun nama asli Sumba, akan memengaruhi identitas kita. Jika bahasa daerah tersebut punah, maka jati diri dan kebudayaan kelompok penutur juga hilang. Masyarakat akan kehilangan kemampuan untuk memahami kearifan lokal dan pengetahuan tradisonal yang memiliki nilai dan manfaat tinggi untuk masa sekarang. Jika nama Sumba hilang, masih berani kita sebut diri kita sebagai putra dan putri Sumba yang lahir dari rahim tanah Marapu? Omong-omong tentang Marapu, semoga Sumba masih bisa disebut Tana Marapu untuk sekarang dan di masa depan.
Terakhir, ada video yang pernah saya buat beberapa tahun lalu, saya kira ini masih bisa untuk ditonton:


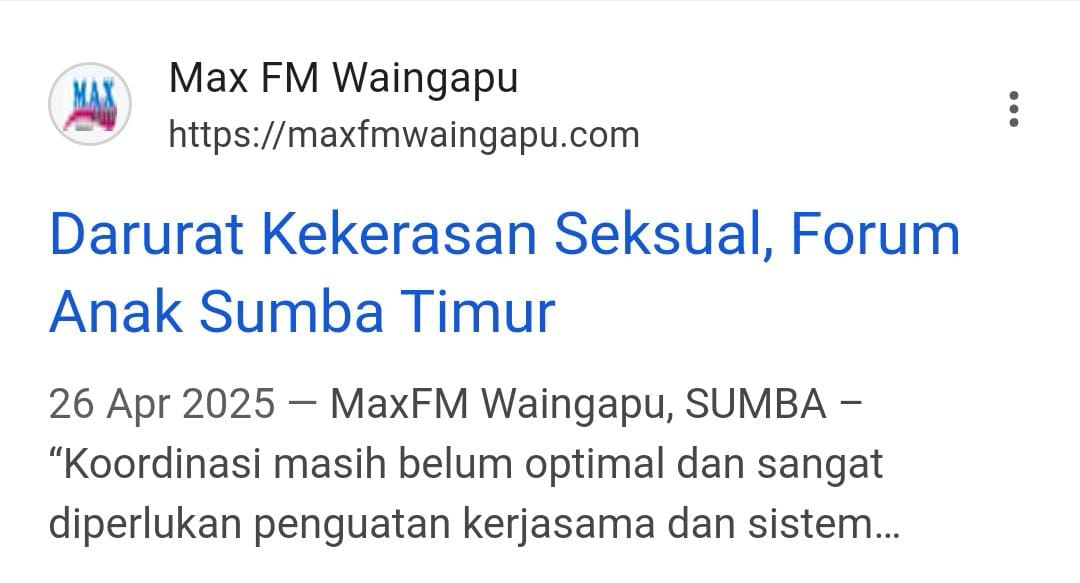
Comments
Post a Comment