Orang Sumba, Kuasa Modal dan Rasisme yang Lahir dari Ketimpangan Sosial di Sumba Timur
Namun, di sisi lain, ketika video seorang gadis yang diduga mencuri di salah satu toko di Kawangu (info dari teman; anak tersebut mengidap kleptomania), mendapat perlakuan yang melukai nurani, dan disusul kasus kekerasan terhadap seorang pekerja perempuan di salah satu toko di Kambaniru yang viral sejak dini hari 16/12/2025, membuat persoalan ini perlahan berubah dari isu kemanusiaan menjadi isu rasial yang berbahaya.
Kita mungkin berpikir bahwa rasisme ini hanya soal kata-kata kasar atau hinaan berbasis identitas. Namun, rasisme yang terjadi belakangan ini adalah cara berpikir yang menyederhanakan manusia menjadi label-label asal-usul, mulai suku, ras, pendatang, atau pribumi. Rasisme bekerja ketika satu peristiwa individual digeneralisasi menjadi watak kolektif suatu kelompok. Dan, sayangnya, itu datang dari kita orang Sumba yang punya nilai "patembi."
Dalam konteks ini, rasisme menjelma bukan karena orang Sumba membenci etnis tertentu sejak awal, melainkan sebagai reaksi atas pengalaman berulang: dimaki, dipermalukan, dipukul, dan direndahkan martabatnya oleh mereka yang memiliki kuasa ekonomi.
Kasus di Kawangu dan Kambaniru sejatinya bukan soal etnis, melainkan soal kekuasaan. Relasi antara pemilik modal dan pekerja yang timpang memungkinkan kekerasan terjadi dan dinormalisasi. Ketika seorang perempuan muda dimaki dengan kata-kata kasar, tubuhnya dijadikan bahan ejekan, atau ketika seorang pekerja dipukul dan dicukur rambutnya, yang bekerja di situ adalah kuasa, bukan identitas ras. Sayangnya, kemarahan atas kekerasan itu kemudian diterjemahkan secara simplistik menjadi sentimen orang Cina versus orang Sumba. Maka, bilamana kita menggeser fokus dari kekerasan itu sendiri ke identitas rasial, saya kira ini justru berisiko mengaburkan akar persoalan yang sesungguhnya.
Saya membaca komentar-komentar di Facebook, yang, mayoritas saya temukan dalam grup besar di Waingapu, mulai dipenuhi narasi orang pribumi,
pendatang, orang lokal, orang Cina, dan orang Sumba. Narasi semacam ini berbahaya karena mengaburkan pelaku dan sistem yang sebenarnya bermasalah. Ia menggeser fokus dari tindakan kekerasan dan relasi kerja yang eksploitatif menjadi konflik identitas, seolah-olah semua orang Cina adalah penindas, atau semua orang Sumba adalah korban. Pola pikir seperti ini tidak menyelesaikan apa pun, justru memperlebar jurang sosial, karena ini sangat rentan memantik konflik horizontal. Dan, ini mengerikan, kawan-kawan.
Membela orang Sumba sebagai korban kekerasan adalah keharusan moral atas nama kemanusiaan. Kekerasan harus dilawan dengan hukum, solidaritas, dan kesadaran kelas, bukan dengan kebencian berbasis ras. Jangan sampai empati kita dikalahkan oleh sentimen kelompok, karena kalau anpai itu terjadi, yang lahir bukan keadilan, melainkan dendam kolektif.
Terlepas dari itu semua, terima kasih atas solidaritas kita semua, solidaritas tau Humba yang kuat, sebab kita semua adalah keluarga. Nyutta pa-kalembingu. Maka, mari membantu korban sebaik dan sebisa yang kita mampu.


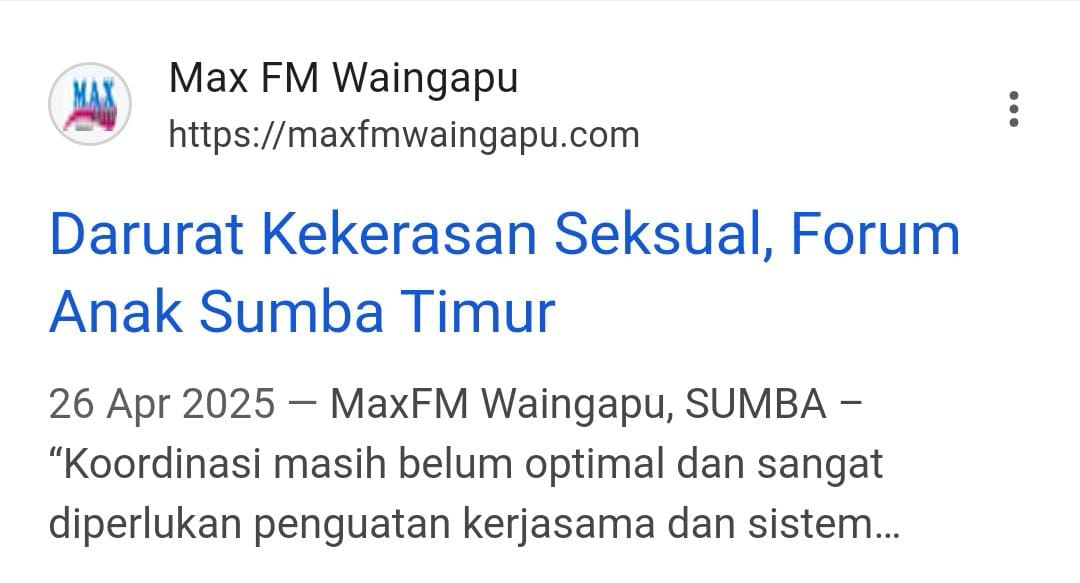

Comments
Post a Comment