Luka itu Sirna di Makam Mahaguru Puisi
Saya mengenal 'Hujan Bulan Juni' dari Sapardi Djoko Damono. Sosok yang tidak pernah saya jumpai, bahkan dalam rupa buku. Saya mengenal 'Hujan Bulan Juni' lewat status-status yang berkeliaran di beranda Facebook, di story WhatsApp, di feed Instagram dan lewat utas pada Twitter. Sesekali, saya memastikan, bahwa 'Hujan Bulan Juni' itu memang milik Opa Sapardi melalui penelusuran Google. Singkatnya, saya mengagumi Opa Sapardi melalui puisinya.
Namun, tulisan ini bukan tentang beliau. Tulisan singkat ini, adalah kisah (mungkin refreksi pribadi) yang coba saya bagikan. Semoga ada yang baca😁
Sabtu, 3 April 2021.
Saya baru saja bangun pagi saat teman saya mengirimkan pesan singkat yang diteruskan melalui pesan WhatsApp.
"Sudah lingsir," katanya. "Jumat Agung beliau puasa 3 hari, dan langsung drop, 2 hari lalu sempat nelpon, tanyakan kartu bpjs (padahal kartunya sudah dibawa). RIP: Umbu Wulang Rambu Paranggi."
Mata saya belum benar-benar terang saat foto yang ikut bersama pesan singkat itu loadingnya cukup lama. "Ya Tuhan, dosa apa saya semalam, sampai paket internet saya lelet."
Hari itu masih pagi, saat semesta menjemput Umbu Landu Paranggi, yang kata orang-orang, beliau adalah Sastrawan legendaris Indonesia, Mahaguru Puisi, Penyair, dan Presiden Malioboro_sebuah julukan atas apresiasi sastra di jalanan Malioboro yang kemudian melahirkan nama-nama besar dalam sejarah sastra Indonesia, seperti Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, Korrie Layun Rampan, Yudistira Ardhi Nugraha, bahkan Agus Dermawan T dan Ebiet G Ade.
Nama-nama itu sering saya baca, bahkan beberapanya sering saya lihat di TV. Tapi Umbu, bahkan tak banyak yang tahu, bahwa beliau adalah Mahaguru Puisi. "Di Uzbekistan, ada padang terbuka dan berdebu. Aneh, aku jadi ingat pada Umbu. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka. Di mana matahari membusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka. Bilamana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga," begitu bunyi penggalan puisi 'Beri Daku Sumba' karya Taufik Ismail, seorang penyair dan sastrawan Indonesia.
.
Saya menulis ini dengan penuh penyesalan. Sebab, selama hampir 4 tahun kuliah di Bali, saya belum pernah berjumpa dengan Umbu Landu Paranggi_Mahaguru Puisi yang lahir di Sumba, tempat kelahiran saya. Saya menulis ini dengan penuh penyesalan. Sebab, beberapa kesempatan berjumpa dengan beliau, tidak pernah saya wujudkan.
Setelahnya, saya menulis ini dengan penuh harapan. Sebab, Mei kemarin, saat patah mulai menyerang, saat raga sudah tak kuat lagi merawat hati yang kian terkikis, saya menemui Mahaguru Puisi itu di makamnya. Dalam patah, tanpa doa, saya tidak bisa berkata-kata. Di makam Mahaguru Puisi, saya tidak banyak bicara, tidak berdoa, hanya datang dan mengambil foto dengan tangan gemetar. Sambil berharap, suatu saat, saya akan menulis untuk orang yang kepadanya, janji ini telah didaraskan.
Di makam Mahaguru Puisi, ziarah yang batal itu saya tuntaskan. Bukan secara langsung, melainkan lewat keinginan yang sempat terdengar. Di makam Mahaguru Puisi itu, ada harapan yang terus memberontak, menggugat jemari, menggoda hati, untuk terus menulis. Di makam Mahaguru Puisi itu, ada doa yang dipanjatkan. Dalam diam. Dalam hening. Seperti kita:
"Suatu saat nanti, aku akan menulis kisah tentangmu. Tentang kita yang menentang takdir, di mana ada ratap dan doa yang datang bagai badai. Suatu saat, kisah itu akan jadi cerita paling indah yang dibanggakan, bahwa pernah dua insan menusuk-nusuk Tuhan di ujung langit, hanya agar dapat bersama."
.
.
Denpasar, Juni 2021, bukan tentang puisi.


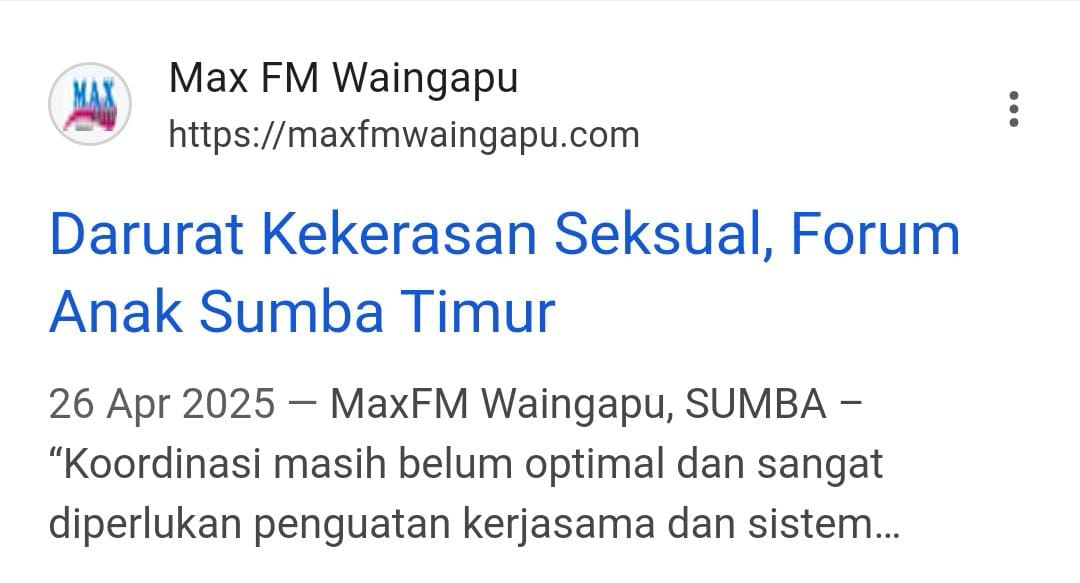

Keren👍👍👍👍👍
ReplyDeleteSaya jadi terinspirasi dari tulisan, kk.. Saya juga mau jadi penulis, tapi masih dalam tahap belajar sekarang ini..