Humba Menuju (bukan) Tana Marapu!?
Humba Tana Marapu."
Sebagai orang Sumba, kita pasti pernah atau sering mendengar orang-orang yang berkata demikian, baik dalam tulisan maupun dalam lisan. Sebuah frasa yang menunjukkan kebanggaan pada tanah kelahiran, di mana dulunya memang benar-benar tanah para Marapu.
Belakangan, frasa ini barangkali hanya menjadi frasa penghias seremonial ucapan-ucapan omong kosong kita. Semoga saja tidak demikian. Namun, dalam evaluasi tahunan Badan Pengurus Marapu, seperti yang saya kutip di status Instagram Ibu Pendeta Herlina Ratu Kenya, sekretaris Bappeda Sumba Timur menyebutkan bahwa terjadi penurunan jumlah warga Marapu yang sangat signifikan hingga sekarang menurut catatan terakhir tahun 2021 tinggal 15 ribuan jiwa.
"Padahal tahun 2016 saat saya mengumpulkan data untuk tulisan akhir saya di UKDW, jumlahnya masih 33 ribuan," kata ibu pendeta dalam status terbarunya tanggal 23 Januari 2023. "Maka, pertanyaannya adalah, 17-an ribu itu ke mana?" Saya mengutip ini karena pertanyaan yang sama telah ada sejak beberapa tahun terakhir, melihat kita begitu bangga akan frasa "Humba Tana Marapu," tapi di sini lain, juga sangat bangga agar orang-orang Marapu tidak lagi menjadi Marapu.
"Salah satu pengurus penghayat memberi tanggapan katanya, di KTP mereka beragama lain, karena terpaksa - seperti pengalamannya terpaksa menjadi Kristen demi sekolah - tapi dlm keseharian mrk tetap Marapu," demikian kata ibu pendeta dalam statusnya. "Sungguh suatu kenyataan yang perlu disikapi dengan serius sebab di kalangan agama, Marapu masih dipandang sebagai obyek Pl atau dakwah, padahal mereka adalah penyembah Tuhan dengan cara yang berbeda dan itu telah final diputuskan dalam negara melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016."
Sampai di sini, saya masih belum percaya, bahwa kita yang teriak-teriak mayoritas - minoritas pada kesempatan tertentu menyaksikan pemberitaan tentang mayoritas di negeri ini, padahal sama saja. Kita pun adalah mayoritas yang enggan mengakui bahwa kita kerap berlaku demikian.
Salah satunya, orang-orang Marapu disebut simpatisan. Padahal, kita juga sering mendengar cerita bahwa orang-orang Marapu rela memberikan tanahnya dengan cuma-cuma hanya untuk membangun gereja. Namun, cerita mereka hanya sebatas cerita hingga akhirnya mereka masuk menjadi bagian dari anggota agama tertentu. Tentu saja masuknya mereka berpartisipasi dalam angka penurunan jumlah penduduk Marapu yang sangat signifikan. Namun, siapa yang kan disalahkan? Atas nama mewartakan kabar gembira keselamatan, kita tentu tidak akan merasa bersalah. Sama sekali tidak menganggap itu bukan sebuah kesalahan.
Bayangkan ada lebih dari 4000-an agama yang ada di dunia. Bila satu saja menganggap bahwa yang dianutnya adalah yang paling benar, hingga mengharuskan agar yang lainnya masuk menjadi satu dengannya, maka, ada berapa banyak jiwa yang tidak diselamatkan? Bila surga, bila memang itu ada, hanya dikhususkan untuk agama tertentu, maka akan ada jutaan jiwa yang mati, masuk neraka. Ah, kejam sekali.
Semoga Humba Tana Marapu tetap menjadi Humba yang orang-orang Marapu-nya tetap ada, tidak dipersulit membuat surat ini dan itu, dan tetap diakui sebagai pemeluk agama yang sah di republik ini. Semoga. Amin.
Akhir kata, saya tutup dengan pertanyaan refleksi yang saya kutip dari tulisannya almarhum Om Alex yang judulnya Melestarikan Marapu: Saya kadang berpikir, jangan-jangan agama Katolik (yang saya yakini) yang datang belakangan ke Sumba, sudah ikut "merusak" Marapu? Atau justru mengukuhkannya?
.
Nb: Baca juga tulisan lainnya yang berkaitan:
1. Tahun 2019, seseorang dalam sebuah grup Facebook membagikan protesnya karena anaknya yang masih agama Marapu dimasukkan ke sekolah, tapi tidak diterima. Setelah menulis ini, postingan tersebut dihapus, tapi tulisan saya biarkan saja
2. Gambaran pemerintah kita tentang Marapu


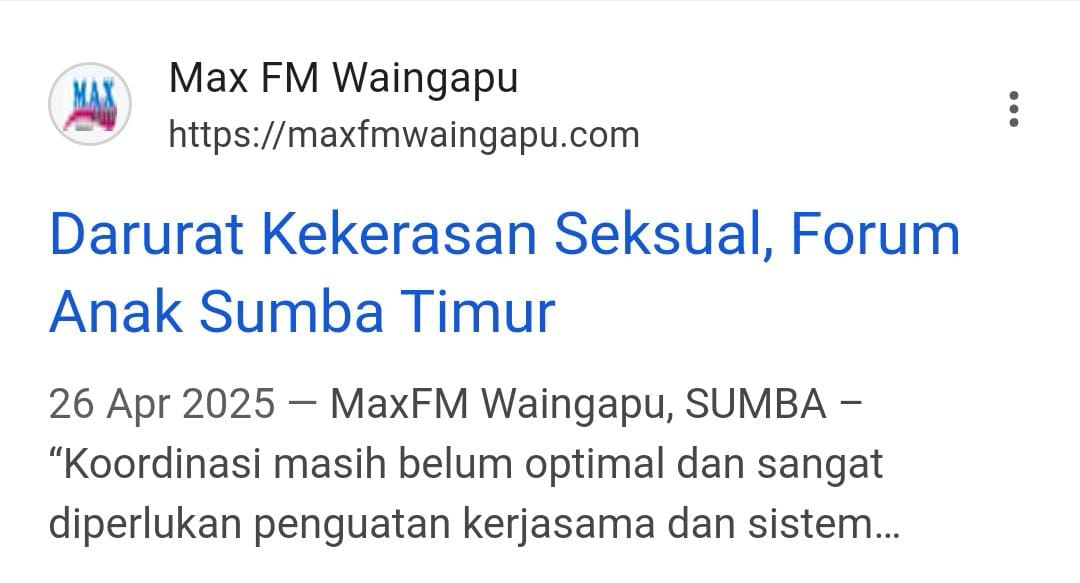

Comments
Post a Comment