Koenpan
Koenpan.
Ada yang menyebutnya Kota Karang. Ada pula yang menyebutnya Kota Kasih. Konon katanya, gugusan karanglah yang membuatnya dijuluki Kota Karang. Sedang Kota Kasih, karena memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Barangkali inilah sebabnya, tempat ini dijadikan kota sekaligus Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang, kata orang, Nusa Tinggi Toleransi sebagai kepanjangan lain dari akronim NTT. Sebuah narasi yang umumnya ada di kolom-kolom komentar media sosial, yang, tentu saja membentuk persepsi kita menjadi orang-orang baik.
Ya, kita memang hidup di provinsi penuh toleransi. Salah satu sebabnya, yang tidak banyak dibicarakan adalah karena kita enggan membaca hal-hal buruk, semacam 'demi nama baik' apapun itu tidak akan kita hiraukan. Kita tidak suka membaca diskriminasi mayoritas yang adalah kita terhadap minoritas. Kita tidak mau membaca kekacauan demi kekacauan yang sebabnya sederhana, beda suku. Kita pun tidak mau membaca betapa asyiknya aparat ketika berhadapan dengan warganya sampai ada ibu-ibu bertelanjang dada. Kita..., tidak jadi. Saya mau menuliskan pengalaman saya yang asyik-asyik saja.
Tiba di sini, selain lu, beta, dan sonde yang sudah di luar kepala, kata pertama yang saya ingat adalah "Uisneno Nokan Kit," yang, sering sekali saya lihat di surat undangan. "Tuhan beserta kita," demikianlah artinya. Saat saya menanyakan kebenaran artinya pada seorang teman, ternyata benar. "Tuhan memberkati kita," katanya, lalu disusul, "Tuhan bersama kita." Beda sedikit dengan yang saya tahu, tidak apa-apa, yang penting Tuhannya sama. Sama-sama belum pernah dijumpai.
Hari pertama tiba, saya dijemput oleh teman saya, Sipri, lalu beristirahat sejenak di rumahnya, karena waktu datang dari rumah, kepagian. Bayangkan! Dua jam sebelum jam 6.30, itu berarti saya harus siap dan sudah harus berangkat sebelum jam 4.30 hanya karena berpegang teguh pada kata on time. Sialnya, selalu berakhir sama, bahwa disiplin waktu itu, merugikan apabila yang lainnya tidak ikutan.
"Oh, itu sudah karang yang dorang bilang kota karang?" Belum selesai dijawab, saya bertanya lagi, "kok tidak seperti yang saya bayangkan, ya? Kota karang yang dorang bilang." Lagi, sebelum dijawab dan saya tidak dengar betul karena suara kendaraan dalam perjalanan, "oh, ternyata begini e."
Untuk menguatkan dugaan, ah bukan, pertanyaan dan kenyataan yang ada, saya lagi-lagi bertanya. Kali ini ditujukan pada tuan rumah, orang Koenpan. "Kenapa di sini tidak ada karang?" tanya saya pada Enn saat dia datang sebagai pengunjung menuju tengah malam. Saat itu, saya hendak akan makan malam, yang, baru saja tiba dari grab. Namun, dibatalkan, eh maksudnya, saya batalkan makan malam karena harus bertemu tamu yang adalah tuan rumah.
"Yang benar Koenpan atau Koepang?
"Kopan, sih."
"Tapi b baca Koenpan a."
"B sond tau yang benar mana."
Tentu saja cerita dan proses pertemuan ini tidak saya tuliskan secara benar dan rinci, sebab harus ada seseorang yang lain yang datang. Dan, benar saja. Hampir setengah sebelas, barulah datang Lis Morib dengan sejuta pisang gorengnya yang memakan waktu berjam-jam sejak ditelfon pertama untuk datang.
Sungguh, sebagai tamu, saya sangat senang dijamu oleh tuan rumah dengan pisang goreng. Ini mungkin akan menjadi satu-satunya hadiah yang saya peroleh di tempat ini. Kalian bisa bayangkan, kan? Hanya pisang goreng! Tidak ada air, tapi untungnya saya masih bisa bernafas, tanpa ada sesuatu yang sesak di tenggorokan. Berkat pinjam air di tuan rumah, tentunya.
Anggap saja kalimat-kalimat di atas adalah luapan ekpektasi yang nyaris tidak seperti yang dibayangkan. Saya membayangkan makan sei babi, yang, kata orang rasanya beda. Entah masuk di jenis rasa yang mana ini rasa beda, tapi ya, begitulah. Itu hanya berupa bayangan sampai akhirnya mencicipinya langsung. Karena itu, bila ada yang sakit hati kecewa dan marah, karena ada pendatang yang makan babinya tuan rumah, jangan sungkan-sungkan untuk tambahkan lagi nanti bila saya ke sini lagi.
"Maaf suh e, saya makan kalian pu babi."
"Itu bukan kami pu babi. Bisa saja itu babi dari tempat lain lalu dikirim ke sini."
Hari kedua, tidak ada janji yang ditepati. Semuanya hilang ditelan kantuk dan malam. Apapun yang ada di pikiran, hilang seketika. Tidak ada cerita yang ingin diceritakan. Duduk lebih dari 9 jam sudah banyak menyita waktu. Lebih baik tidur. Buka mata tutup mata, tiba-tiba sudah hari terakhir. Tidak banyak yang saya tahu di tempat ini. Padahal, waktu hendak ke sini, ada banyak hal yang saya rencanakan. Orang-orang dan tempat-tempat yang harus dikunjungi, makanan yang harus dinikmati dan tentu saja, menikmati segala yang perlu dinikmati, yang, tidak terlaksana dengan baik, memang harus diakhiri.
"Karang saja sonde sempat lihat, apalagi yang mau diharap," demikian pesan ejekan terakhir yang saya dapat.
Dalam perjalanan menuju tempat yang kata orang ramai tiap malam Minggu, depan Aston Hotel, saya kembali membayangkan bahwa betul NTT itu Nusa Tinggi Toleransi, ketika satu motor tiba-tiba saja menyalib kami dari sisi kiri. Ngebut dan bikin kaget. Beberapa saat kemudian, satu lagi. Untung saja ini yang terakhir.
"Biasa orang Sumba dorang bafoto di sini."
"Karena? Rame?"
"Karena di Oesapa gelap. Di sini ramai dan terang."
Pada akhirnya, di lebih dari pukul sepuluh, saya ke Oesapa juga. Dijemput oleh Sipri di hotel, lalu menuju pantai Oesapa menjumpai dua teman yang waktu lalu mengunjungi saya di pelataran parkir hotel. Kurang lebih sejam hanya membahas hal-hal tidak penting sebagai basa-basi terakhir sebelum pulang.
Oh, iya, Koenpan. Saya sebenarnya mau tulis ini, tapi melebar ke mana-mana. Karena itu, saya akan memulainya lagi. Koenpan. Dulu, duluuuuu sekali. Sebelum Koenpan berubah menjadi Kupang, Raja Koen Bissi II atau Koen Am Tuan memberi perintah untuk membangun pagar batu yang mengelilingi istana kerajaannya.
Pagar batu itu dibikin berlapis-lapis, sampai lapisan keempat. Empat lapisan batu ini dalam bahasa Helong disebut Pan. Orang-orang yang hendak menemui Raja Koen harus melewati Pan, pagar batu yang mengelilingi istana raja. Mereka, kemudian menggunakan istilah Koenpan jika ingin menemui Raja Koen.
Lambat laun, istilah Koenpan berubah menjadi Koepang, dan akhirnya menjadi Kupang, yang menyesuaikan dengan ejaan baru, bahasa Indonesia. Daaaaaan, lu tau ko sonde, pas tiba di ini tempat, b suh diajak balogat Kupang nih. Kan.... kan.... kan.... b sond bisa 😥😅


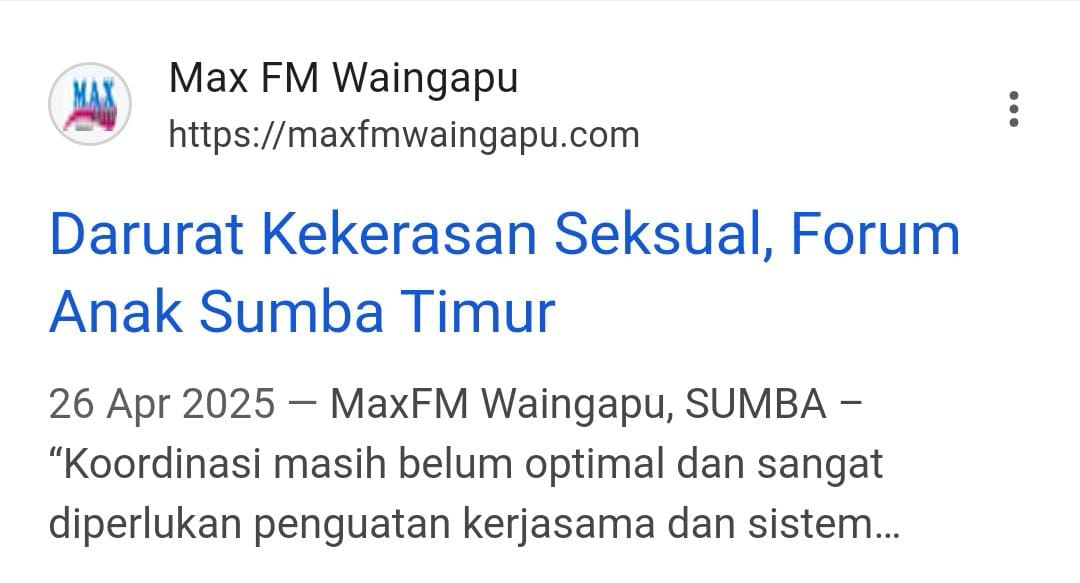

Comments
Post a Comment