Mahasiswa, Sampah! dan Kebijakan Pemerintah
Rima Melani Bilaut mengomentari story WhatsApp saya siang tadi. "Jangan terlalu salahkan orang yang buang sampah sembarangan," katanya. Satu menit kemudian, saya membalasnya. Iya, satu menit. Waktu yang sangat singkat untuk proses berpikir yang cepat. Apalagi, yang mengomentari story saya adalah seorang Rima.
"Mau salahkan yang jual sebenarnya, tapi dorang suh bayar uang sewa kantin," balas saya beralibi.
"Bukan salah yang jual juga," katanya menghardik alibi saya. "Orang cuman cari hidup dari sana."
"Salah produsen?"
Sementara bertanya demikian, jempol saya menari mencari tombol hapus untuk menghilangkan jejak story yang saya tulis tadi agar tidak dibaca orang lain. Namun, apa daya. Sudah lebih dari 20 orang membacanya meski sudah saya hapus.
"Kita terlalu sering berdiskusi tentang sampah hingga lupa membuang sampah pada tempatnya," demikian alasan yang sering saya gunakan bila ada diskusi tentang sampah dan hasilnya begitu-begitu saja.
Demikian penggalan pertama story saya. Rasanya, itu tidak apa-apa dan baik-baik saja. Setidaknya itu yang menjadi sangkaan saya. Tapi, penggalan kedua dan ketika rasanya bermasalah. Dan komentar Rima itu bisa jadi datang dari sana. Semoga tebakan saya benar adanya.
"Kebijakan kampus, kebijakan pemda, kebijakan pemerintah nasional. Kalau kebijakannya hanya bersih-bersih saja dan pengadaan tempat sampah, ya orang akan terus buang sampah," katanya menjawab pertanyaan saya tadi. "Masyarakat kayak kita cuman terjebak sistem yang lebih besar, sedikit salah sasaran kalau masalah sampah bebannya paling banyak kepada konsumen. Kau mau jadi konsumen sadar pun tidak akan menghentikan laju produksi barang yang akhirnya berujung sebagai sampah."
Sehabis itu, ia berkata lagi, "Saya sarankan (nonton) film kampanye Story of Stuff biar paham alurnya," balasnya semenit kemudian. "Ada di youtube, silahkan dicari." Tak lama kemudian, setelah saya mengirimkan screenshot beberapa video (yang mungkin berbahasa Inggris), ia kemudian mengirimkan saya sebuah link google drive berbahasa Indonesia.
Kemudian, saya menonton video kampanye itu:
Video tersebut diawali dengan seorang perempuan yang kalau tidak salah memegang sebuah headphone. Lalu berkata, "Pernahkah terpikirkan (oleh kita) dari mana asal barang kita dan ke mana perginya ketika kita buang?"
Sejenak, saya berhenti menonton video itu lalu mengetik kembali pertanyaannya untuk memastikan, bahwa barang-barang yang setelah digunakan tadi dalam story WhatsApp yang dikomentari oleh seseorang itu, ke mana larinya? Ditinggalkan di atas meja kah? Dibiarkan begitu saja kah? Atau diapakan?
"2034 sebentar lagi. Kurang dari 15 tahun. Waktu yang cukup untuk menertibkan mahasiswa agar bisa setidaknya membuang sampah pada tempatnya sehabis makan," begitu lanjutan caption pada story WhatsApp saya siang tadi. "Oh tidak. Saya lupa, bahwa di kampus swasta, mahasiswa/i boleh makan tanpa membuang sampah makanannya pada tempat sampah berjarak kurang lebih satu meter."
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melanjutkan aktivitas menonton video kampanye yang sempat tertunda tadi.
Dari 100 ekonomi terbesar di bumi, 51% adalah milik perusahaan. Dan ketika perusahaan membengkak dalam artian finansial, maka kekuatan perusahaan juga ikut membengkak. Akibatnya, terjadi perubahan sikap dari pemerintah yang sebelumnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, beralih pada kepedulian pada perusahaan dengan segala modalnya itu.
Hal itu berimbas pada terjadinya eksploitasi berlebih oleh perusahaan-perusahaan. Dengan berdalih bermodalkan investasi, sumber daya alam yang ada dikeruk agar memperkuat modal perusahaan. Dalam sepertiga dekade terakhir, berdasarkan video kampanye itu, dijelaskan, bahwa sepertiga dari sumber daya alam dihabiskan. Hilang akibat ulah manusia yang menebang, menambang, membongkar dan menyampahi bumi. Kita meremehkan cerita, bahwa bumi seharusnya menjadi ruang hidup manusia.
Kita tahu, bahwa pengadaan barang, dimulai dari produksi, lalu ke distribusi, kemudian bermuara pada konsumsi, dan terakhir dibuang. Namun, masalahnya juga berasal dari situ. Apa yang kita produksi adalah racun bagi kita, yang kemudian kita keluarkan juga dalam bentuk racun bagi sesama dalam proses distribusi yang lebih cepat. Kemudian, membuangnya. Ekonomi barang selalu berjalan seperti itu. Setelah dikonsumsi, dibuang.
Ah, sial. Saya tidak bisa menyederhanakan bahasa saya untuk menjelaskan bagaimana kita, yang begitu konsumtif ini menahan laju distribusi. Kita telah menjadi negara tukang belanja. Saya tahu kalimat ini seharusnya ditujukan pada penduduk Amerika, tapi, sejauh pengamatan saya, kita pun demikian. Bukan hanya negara, tapi juga masyarakatnya yang super konsumtif.
"Ekonomi kita yang sangat produktif menuntut agar kita menjadikan konsumsi sebagai cara hidup kita, agar kita merubah pembelian dan penggunaan barang sebagai ritual, agar kita mencari kepuasan spritual dan ego dalam konsumsi. Kita perlu hal-hal yang dikonsumsi, dibakar, diganti dan dituang pada laju yang terus dipercepat."
Sampai di sini, saya membayangkan lagi sampah-sampah makanan yang selesai digunakan disimpan begitu saja di atas menjadi tadi. Karena memang, barang-barang tersebut dirancang untuk menjadi sampah. Digunakan lalu dibuang. Menjadi sampah.
Iklan pada media-media massa juga berpengaruh pada kebiasaan kita meneruskan upaya penciptaan "rancangan barang untuk dibuang". Iklan-iklan yang kian massif mendorong budaya konsumtif kita untuk semakin mengkonsumsi barang baru. Lalu membuang barang lama yang sebetulnya masih berguna.
Barang-barang yang dibuang itu kemudian berakhir pada tempat pembuangan sampah, yang sialnya, bisa berakhir pada pembakaran. Di sini, masalah baru tercipta lagi. Sampah-sampah yang dibakar menggunakan teknologi pengolahan sampah memunculkan racun bagi makhluk hidup. Sebab, sampah yang dibakar menggunakan teknologi itu mengubah sampah menjadi gas sisa hasil pembakaran berupa dioksin.
Dioksin adalah zat beracun hasil pembakaran atau residu dari pembakaran sampah, seperti plastik yang bercampur unsur halogen. Racun ini bertahan lama dalam tanah 10-12 tahun. Ketika terhidup oleh manusia dalam bentuk gas yang mudah menyebar, maka akan menimbulkan reaksi seperti batuk dan sesak nafas. Baik jika hanya itu saja. Bila mengakibatkan kanker, bagaimana solusinya?
Sama seperti jawaban Rima Melani Bilaut tadi, solusi untuk permasalahan ini ada pada pemangku kebijakan, pemerintah. Kebijakan pemda, kebijakan pemerintah nasional. Kalau kebijakannya hanya bersih-bersih saja dan pengadaan tempat sampah, ya orang akan terus buang sampah. Membeli barang, kemudian membuang sampahnya, lalu memberi barang baru lagi, untuk kemudian dibuang. Begitu saja terus sampai kucing bertanduk.
Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang membuang sampah sembarang. Sebab, masyarakat seperti kita ini cuman terjebak sistem yang lebih besar, sedikit salah sasaran kalau masalah sampah bebannya paling banyak kepada konsumen. Kalau kita mau jadi konsumen sadar pun tidak akan menghentikan laju produksi barang yang akhirnya berujung sebagai sampah.
.
Sekian dan terima kasih sudah membaca!


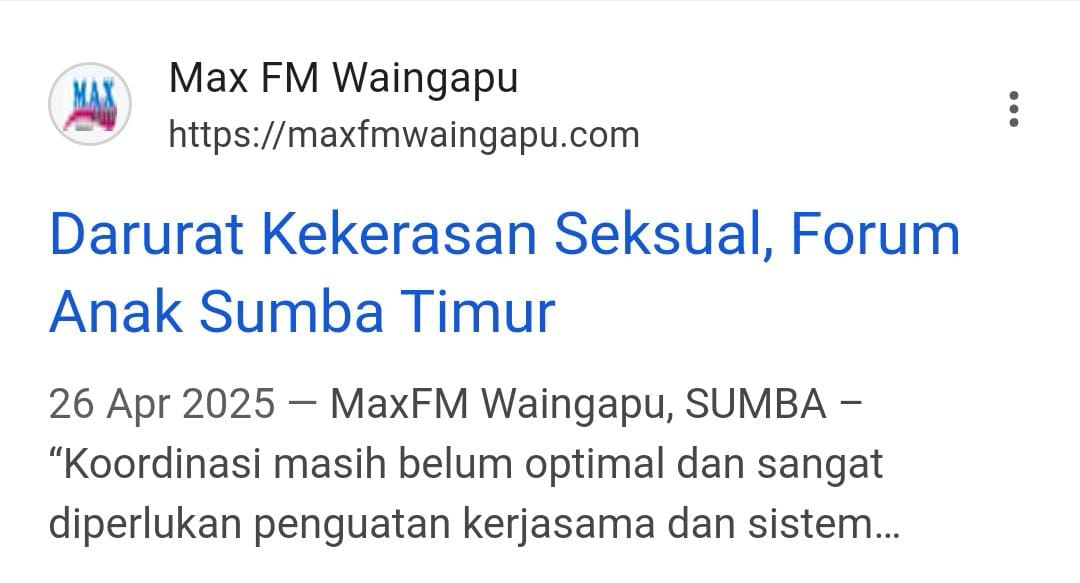

Comments
Post a Comment