Sebab 'hidup bersama' Sudah Terlalu Mainstream.
Aku baru saja terbangun dari tidur, saat sesuatu menyelinap masuk ke dalam pikiranku. Masuknya bukan melalui kepala, bukan juga melalui lubang hidungku. Apalagi melalui mulut. Entah dari mana sesuatu ini datang, yang jelas, seseorang telah mengirimkannya untukku.
Aku ingat jelas malam itu, ketika segala sesuatu yang pernah tersimpan dalam pikiranku, perlahan pecah, hancur dan hilang satu persatu. Bahkan, hilangnya tak menyisakan apa-apa lagi. Semuanya seakan lenyap bagai ditelan bumi. Puncaknya terjadi pada moment pergantian tahun baru. "Seseorang telah menggantikannya dengan sesuatu yang baru," gumamku. "Sesuatu yang begitu kuat, hingga dengan mudahnya ia gantikan yang pernah coba kusimpan."
Sesuatu yang baru itu memang begitu kuat. Ia mampu menghapus segala memory dalam ingatanku. Lalu, tumbuh. Ia tak bernyawa, tapi hidup. Hidup seakan mati. Ia tak berbentuk, tapi berwarna. Warnanya hijau, juga sedikit hitam. Terkadang, hitamnya lebih kuat daripada hijaunya.
Sesuatu yang baru itu telah menjadi kekal dalam ingatanku. Ia membentuk pikiranku dengan bahasa-bahasa cinta, ia mengikat aku dengan sesuatu yang indah, yang tidak bisa kuterjemahkan dalam logika. Ia membangun peradabannya dari dalam pikiranku. Kemudian, membentuk ritual yang membebaskan karat pada isi hati dengan berkurbankan sebuah ketulusan. Lalu mengucapkan kata, "Selamat tidur tuan kaktus."
Sesuatu yang baru itu terus saja membuaiku dalam ketenangan, kemudian menjadikanku makhluk paling adiktif. Aku yang pernah kehilangan harapan dan hanya berharap yang biasa-biasa saja, dibuatnya terasa istimewa. Aku belum pernah sebersyukur ini sebelumnya. Aku belum pernah merasakan kebahagiaan semacam ini sebelumnya. Di sini, bahagia itu sederhana, ternyata memang sesederhana ia memperlakukanku.
Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai hilang, bukan karena dihilangkan. Bersyukur itu perlahan mulai pudar, bukan karena tidak disyukuri. Mereka telah dicuri orang. Oh, tidak. Mereka tidak dicuri orang. Tapi sesuatu yang pernah masuk dalam pikiranku memberontak ingin keluar. Kekuatannya masih sama seperti saat ia masuk. Namun, apa yang pernah diberikannya masih tersimpan. Mereka tidak ke mana-mana. Tak akan kuberi pada siapapun, bahkan ketika dengan paksa diminta atau dihancurkan dari ingatanku.
Ingatan-ingatan dalam pikiranku menyimpan sejuta warna: rasa, kenangan, tangis dan tawa. Juga sesuatu bernama luka. Dua dari ke lima warna itu ikut memberontak. "Jika sesuatu yang pernah tertanam dalam pikiranmu bisa pergi, mengapa kami tidak?" kata mereka. "Bukankah yang pergi akan ditempatkan pada kotak kenangan yang takkan pernah bisa dijangkau?"
"Kalian tidak pernah tahu bagaimana rasanya setelah memiliki," balas Rasa. Kemudian, Kenangan melanjutkan, "kalian bahkan tidak pernah ingat bagaimana bahagia itu diciptakan dengan menentang takdir."
Seakan tak mau kalah, Tawa juga ikut menjawab, "Bahkan kalian tidak pernah tahu, bahwa lelah, dan capek bisa hilang begitu cepat ketika digantikan oleh senyuman. Bahwa setelah kalian hadir," katanya kepada Tangis dan Luka, "keduanya malah dibuat tertawa."
Aku lupa, bahwa malam itu aku telah diracuni Vius Aku. Aku lupa, bahwa malam itu, adalah yang terakhir aku menyimpan sesuatu yang lain dalam pikiranku. Yang aku ingat, saat ia masuk dalam pikiranku, ia sempat berkata dengan penuh keyakinan, ketulusan dan juga cinta padaku. "Inginku retas obituari ingatanmu dan menghidupkan Virus Aku di sana, agar nama-nama itu error saat kau akses. Lalu kita akan mati bersama, sebab 'hidup bersama' sudah terlalu mainstream."
Ternyata, sesuatu yang masuk dalam pikiranku adalah Virus Aku_yang sengaja diciptakan oleh seseorang di seberang sana. Seseorang yang memiliki tekad yang kuat, seseorang dengan segala keinginannya yang terbuat dari luka, air mata, cinta dan harapan. Virus Aku yang dibuat sama kuatnya dengan dirinya.
Pantas saja aku tak bisa melupakannya. Obituari ingatanku telah diretas oleh Virus Aku dengan penuh ketulusan. Nama-nama yang pernah tersimpan telah lama error, rusak, hancur berkeping-keping, bahkan hilang dan lenyap seketika. Yang hidup tinggal sebuah nama. Tidak, ia tidak hidup. Ia telah mati dalam pikiranku. Ia telah lama mati. Karena itu, ia tak pernah mau keluar dari pikiranku, bahkan sebagai arwah sekalipun.
Di sana, ia masih dan akan terus menetap. Sampai tua, mungkin? Atau sampai mati. Sebab, katanya, "Kita akan mati bersama, sebab 'hidup bersama' sudah terlalu mainstream."
Suatu saat nanti, aku ingin mengenangnya dalam keabadian kata. Mengabadikan kehidupannya yang ingin mati bersama pikiranku. Aku ingin menuliskannya, bukan dalam bentuk puisi seperti Francesco Petrarca menuliskan tiga ratus enam puluh enam puisi romantis untuk Laura, kekasihnya. Sebab, Petrarca dan Laura tak pernah menyatu dalam keabadian.
Bukan pula dalam bentuk sajak-sajak patah hati. Sebab, ia masuk tanpa mematahkan apapun. Ia masuk dan mengganti yang tidak pernah kuraih, lalu diberikannya padaku sebuah hati yang penuh dengan ketulusan, cinta dan semangat secara cuma-cuma. Maka, ketika ia memaksa keluar, haruskah aku rela?
Ia masih tersimpan begitu anggun dan cantik dalam bingkai ingatanku. Meski aku tahu, bahwa di sana ia tidak bebas. Di sana ia terpenjara. Di sana, ia menumbuhkan rasa yang mati. Tapi ia tak pernah menyulut kebencian berkobar dalam nadiku. Malah, sebaliknya, atas nama Rasa, Ingatan dan Tawa, mereka abadi dalam sebuah wadah bernama cinta.
Ia pernah memintaku pergi. Tapi bagaimana mungkin aku pergi, bila ia terus mengikuti dalam pikiranku? Ia pernah pergi, tapi bagaimana mungkin ia berjalan sendiri, sedangkan ia masih tertanam dalam pikiranku? Baik aku, maupun Virus Aku itu, tetap tinggal. Satu-satunya yang dapat mencabutnya dari pikiranku adalah seseorang yang telah mengirimkannya padaku. Mungkin dengan menciptakan "Antivirus Kamu" agar ia bisa melawan Virus Aku.
Tapi bagaimana ia menancapkannya dalam pikiranku? Pertanyaan itu tidak bisa kujawab. Tak bisa diprediksi, sama seperti aku berharap ia tinggal lebih lama dan lama dalam pikiranku, hingga akhirnya ia ingin keluar: Dari pikiran, hati dan nadi: Mati Rasa.
Kemudian katamu,
Kita menciptakan luka...
Lalu mengkambinghitamkan semesta sebagai pemberi luka yang adil...
Seketika itu juga, kata-kataku terbantahkan,
Semesta selalu adil dalam memberi luka: semakin kau menyayangi, semakin kau terluka. "Semakin"nya diberi porsi yang sama. Adil.
.
.
.
Denpasar, 9 Juli 2021| Ruang khayal
.
Ket; tulisan ini dicetak bersamaan dengan tulisan lainnya pada .... .... .....


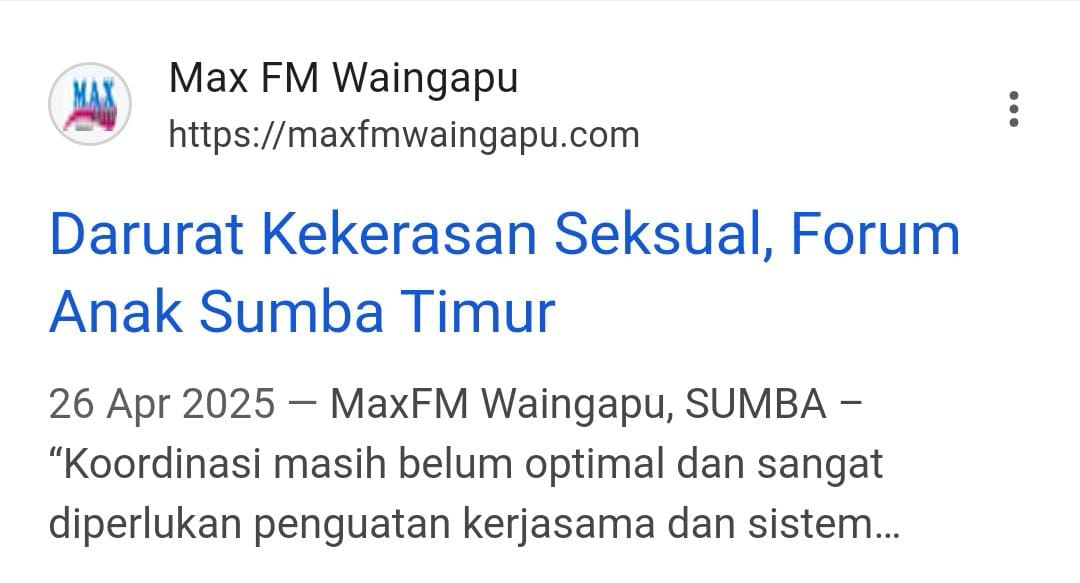

Comments
Post a Comment